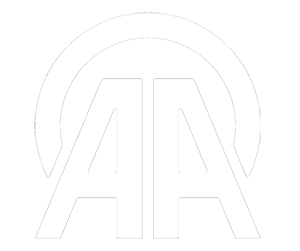Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. (Anton Raharjo - Anadolu Agency)
Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. (Anton Raharjo - Anadolu Agency)
Jakarta Raya
Dandy Koswaraputra
JAKARTA
Entah apa yang akan terjadi dengan rencana migrasi siaran televisi analog ke digital tahun depan. Tahun 2017 hanya tersisa satu setengah bulan lagi, tapi pembahasan revisi UU Penyiaran di DPR belum juga rampung.
Padahal, International Telecommunication Union sudah mengimbau seluruh negara untuk melakukan migrasi digital selambat-lambatnya tahun 2018. Di ASEAN, hanya Indonesia dan Myanmar saja yang belum melakukan migrasi.
Penyiaran digital sendiri adalah sistem penyiaran terestrial free to air menggunakan teknologi digital dengan spektrum lebih sedikit namun menghasilkan gambar lebih jernih. Meski spektrumnya sedikit, namun kanalnya lebih banyak.
Sehingga, dengan migrasi seluruh kegiatan penyiaran ke digital akan ada frekuensi yang tersisa (digital deviden). Frekuensi kosong ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih penting, seperti kebencanaan misalnya.
Tapi yang lebih mendesak, spektrum kosong ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan broadband sehingga industri telekomunikasi bisa berkembang. Saat ini, perkembangan broadband terhambat karena sudah kehabisan slot frekuensi.
Alasan ini yang membuat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengharap RUU Penyiaran bisa disahkan menjadi UU tahun ini. Kalau tidak, maka target migrasi dari analog ke digital 2018 nanti menjadi jauh panggang dari api.
“Saya berdoa agar RUU Penyiaran dapat disahkan menjadi undang-undang tahun ini juga,” kata Agung Suprio, Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Pusat, pada acara Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta baru-baru ini.
Doa adalah upaya. Apa yang menjadi pengharapan Agung merupakan juga upaya dirinya dan institusi KPI agar rencana pemerintah melakukan migrasi siaran televisi analog ke digital menjadi kenyataan.
Namun, doa dan pengharapan semacam itu tampaknya tidak diamini oleh para pencari marjin alias pengusaha media. Mereka lebih senang dengan status quo, kata Bayu Wardhana, Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bidang penyiaran.
“Dengan begitu mereka [pengusaha media] bisa tetap berbisnis menggunakan frekuensi analog yang sekarang mereka kuasai,” kata Bayu kepada Anadolu Agency.
Dengan kata lain, Bayu melihat kepentingan bisnis menjadi penyebab terjadinya tarik ulur antara pemerintah dengan para pemilik modal dalam menyikapi rencana migrasi televisi analog ke digital ini.
Seperti terjadi dua tahun lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATJI).
Putusan pengadilan ini membatalkan aturan tentang TV digital yang dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika, sekaligus menganulir lisensi 33 perusahaan yang telah memenangi tender multiplexing.
Multiplexing atau biasa disingkat mux sendiri merupakan teknik menggabungkan beberapa sinyal analog atau digital menjadi satu frekuensi dalam waktu bersamaan.
Konon, ATJI disponsori salah satu pengusaha media yang tidak mendapat lisensi multiplexing.
Kontroversial sejak awal
Rencana pemerintah melakukan migrasi siaran televisi analog ke digital sejak awal sudah menuai kontroversi hukum. Berbagai pihak, termasuk praktisi dan pengusaha media, menganggap UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 – yang saat ini sedang dalam pembahasan DPR untuk direvisi – tidak bisa mengejar pesatnya perkembangan teknologi, apalagi mengatasi masalah reformasi infrastruktur siaran.
Kontroversi ini berimbas pada perselisihan antara pemerintah dan konglomerat media hingga berujung di meja hijau – seperti sudah disebutkan sebelumnya.
PTUN memenangkan gugatan ATVJI atas peraturan yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyangkut realisasi televisi digital. Menyusul keputusan itu, siaran televisi digital sepenuhnya dilarang. Televisi kembali bersiaran melalui frekuensi terestrial analog, seperti yang saat ini terjadi.
Sebelumnya, Kemenkoinfo – melalui Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2011 – menunjuk 33 perusahaan media sebagai agen multiplexing.
Keputusan pengadilan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi kelangsungan industri penyiaran. Pasalnya, beberapa perusahaan media televisi yang menjadi agen multiplexing sudah terlanjur mengucurkan triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur penyiaran.
Kontroversi tersebut berlanjut hingga kini. Pemerintah dan pengusaha media masih tarik-menarik soal siapa yang berhak menguasai frekuensi digital. Tarik-menarik kepentingan ini terlihat dari molornya pengesahan Revisi UU Penyiaran di DPR.
Salah satu hal yang paling diperdebatkan di DPR dalam membahas RUU Penyiaran adalah apakah penguasaan frekuensi itu diserahkan kepada pemerintah sebagai pengelola tunggal (single mux) atau diserahkan ke beberapa perusahaan swasta (multimux).

Pro-kontra
Melihat pengusaha media yang hanya mengejar kepentingan bisnis untuk menguasai frekuensi publik, menjadi alasan bagi AJI Indonesia untuk mendukung agar hak penguasaan frekuensi tidak diserahkan kepada swasta.
Artinya, organisasi jurnalis ini mendesak agar negara menjadi satu-satunya pihak yang menguasai frekuensi (single mux).
Argumennya, single mux mengembalikan kedaulatan negara atas pemanfaatan frekuensi yang saat ini dieksploitasi oleh televisi swasta, termasuk terlibatnya partai politik di industri media.
Kedua, single mux yang dikelola negara memberikan iklim usaha yang sehat dibandingkan multimux, di mana ada perusahaan yang mengelola pembagian channel sekaligus pengguna channel. Sementara ada perusahaan (pengguna channel) yang menyewa pada perusahaan saingannya.
Ketiga, industri swasta sebaiknya lebih memfokuskan diri pada peningkatan mutu konten siaran. Biar negara yang mengurus pemancar dan menara. Dengan adanya pemisahan antara infrastruktur dan konten, pengelolaan single mux jadi lebih netral.
Namun para pengusaha media melihat lain. Mereka menilai sistem single mux tidak mencerminkan demokratisasi penyiaran. Bagi industri media, sistem multimux atau hybrid adalah pilihan terbaik. Apalagi, infrastruktur swasta sudah siap. Hybrid, dalam hal ini, adalah pembagian penguasaan frekuensi oleh pemerintah dan swasta.
Selain itu, dengan jumlah pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang ada sekarang sebanyak 7 di Jakarta dan 5 di luar kota Jakarta, sistem multimux/hybrid menciptakan sistem penyiaran yang sehat dan kompetitif karena Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) memiliki pilihan, mau bergabung dengan multiplexing LPS atau Lembaga Penyiaran Publik (LPP).
“Disesuaikan dengan service level, layanan yang ditawarkan dan harga sewa,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Neil Tobing.
Menurut Neil, sistem single mux berpotensi menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena terjadi posisi dominan yang membatasi ruang gerak LPS. Negara juga harus membangun infrastruktur multiplexing baru yang dananya sangat besar. Padahal kalau menerapkan multimux/hybrid, LPS pemegang IPP multiplexing sudah membangun infrastruktur.
“Biayanya dari APBN apa pemerintah sanggup?” kata Neil.
Jika single mux yang dipilih, negara harus membayar kompensasi kepada LPS eksisting untuk pengembalian frekuensi kepada pemerintah. Selain itu, karena tidak ada kompetitor sehingga tidak ada benchmark.
“Kalau single mux ini diterapkan, maka akan ada PHK besar-besaran terhadap karyawan LPS di bidang teknik yang mengelola infrastruktur transmisi penyiaran,” ujar Neil.
Menurut dia, sistem single mux juga tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi penyiaran televisi masa depan yang sangat cepat, karena penyediaan teknologi baru memerlukan dana besar. Pilihannya pun sama-sama tak enak: dibebankan kepada mekanisme APBN yang sangat birokratis atau melalui pinjaman luar negeri yang menambah utang negara.
Negara vs mafia
AJI Indonesia, melalui Bayu Wardhana, menyangkal argumen bahwa single mux tidak menciptakan demokratisasi penyiaran. Dia memberi contoh AirNav Indonesia yang menguasai ruang udara Republik Indonesia, dan maskapai-maskapai memanfaatkan ruang udara tersebut seraya bersaing dan kompetisi dalam layanan penerbangan.
Begitu juga dengan penyiaran. Industri TV akan saling bersaing meningkatkan mutu siaran jika penguasaan mux berada di tangan negara.
Menurut Bayu, pada konteks Indonesia, sistem multimux atau hybrid pada akhirnya akan dikuasai oleh grup-grup media televisi besar, seperti Trans, MNC, VIVA dan lainnya yang pada akhirnya akan menutup peluang industri penyiaran baru. Kompetisi jadi tidak berjalan.
“Kartel yang ada, isi siaran pun tak akan berkembang,” kata dia.
Dia juga menampik bahwa dengan penerapan single mux ini akan berakibat pada PHK besar-besaran. Kalaupun PHK harus terjadi, sebut dia, terbatas pada pekerja bagian tower dan pemancar. Sebagian tenaga bisa diserap oleh TVRI yang menjalankan pemancar single mux.
“10 TV swasta itu tetap dapat channel, dijamin undang-undang. Jadi tetap bisa siaran normal. Bagian produksi, berita, infotainment, iklan, dan lain-lain tetap bisa bekerja,” tegas Bayu.
Argumen bahwa single mux tidak mengadaptasi perkembangan teknologi TV masa depan juga tidak benar. Alasan dia, baik single mux maupun multi mux sama-sama ketinggalan jika berbicara teknologi masa depan.
Klaim bahwa single mux tidak memiliki kemampuan menyediakan teknologi terbaru karena persoalan keuangan juga tidak tepat. TVRI dengan dana APBN sudah memiliki teknologi digital di beberapa wilayah siar.
Menurut Bayu, kekurangan pemancar digital di beberapa wilayah dapat diambil dari iuran frekuensi yang dibayarkan sejumlah televisi swasta setiap tahun.
“Pemasukan non-budgeter yang bisa digunakan langsung untuk keperluan penyiaran,” kata dia.
Jalan tengah
Dalam presentasinya di sebuah acara FGD soal penyiaran, Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Pusat Agung Suprio menawarkan alternatif.
Menurut Agung, jika yang terpilih adalah single mux, maka pengelola multiplexing memberikan saluran kepada LPS yang eksisting tanpa melalui tender lagi.
Selain itu, pengelola multiplexing melakukan appraisal terhadap infrastruktur yang dimiliki swasta lalu dikompensasikan dengan semua mux.
Sementara jika yang diterapkan adalah sistem multi mux atau hybrid, harus ada batasan terhadap operator dan penyewa saluran.
Operator perlu menyepakati pengaturan di sektor hulu agar memberikan beberapa saluran untuk televisi yang berformat edukasi dan TV lokal.
Lalu, harus ada kesepakatan jumlah operator milik pemerintah lebih besar atau minimal sama dengan jumlah operator milik swasta.
Jalan tengah yang ditawarkan komisioner KPI ini tidak salah untuk dipertimbangkan para pemangku kepentingan dunia penyiaran di Indonesia, terutama para anggota DPR yang tengah berdebat soal RUU Penyiaran.
Jika menilik persoalan yang ada dalam diskursus berkepanjangan soal penyiaran ini, mungkin opsi jalan tengah ini juga tidak sempurna. Namun setidaknya pilihan moderat ini perlu dipertimbangkan untuk meniadakan yang kalah.
Revisi UU Penyiaran masih tertunda akibat polemik ini. Jika memang benar pengusaha media mainstream justru menikmati penundaan ini, maka tidak salah juga jika dikatakan saat ini negara sedang berhadap-hadapan dengan mafia.
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.